Oleh: Tigaris Alifandi*
Argentina telah meraih dua gelar Piala Dunia, yaitu pada tahun 1978 dan 1986. Dua gelar juara itu diraih dengan menunjukkan dua sisi sepakbola Argentina yang saling bertolak belakang.
Gelar pertama pada tahun 1978 menunjukkan keindahan sepakbola Argentina di bawah ironi otoritarian rezim Jorge Videla. Sedangkan gelar kedua Argentina pada 1986 mencerminkan pragmatisme sepakbola Argentina yang justru tumbuh dalam era baru demokrasi pasca runtuhnya rezim Videla.
Pada 1966, FIFA menunjuk Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia edisi kesebelas tahun 1978. Dua tahun sebelum perhelatan digelar, Jorge Videla dengan latar belakang militernya naik ke puncak kekuasaan setelah melancarkan kudeta terhadap petahana Isabel Peron.
Videla muncul tatkala Argentina diguncang ketidakstabilan politik dan ekonomi. Alih-alih memperbaiki keadaan, rezim Videla justru memimpin dengan tangan besi. Kelompok kiri, yang berseberangan dengan Videla, diculik, dipenjara, dan bahkan dibunuh.
Banyak pihak mengecam kekejaman Videla dan berniat memboikot Piala Dunia 1978. Kita bisa melihat tarik ulur hal ini dalam "FIFA Uncovered" yang baru saja dirilis oleh Netflix. Namun FIFA tetap pada pilihannya. Piala Dunia tetap digelar di Argentina.
Piala Dunia 1978 menjadi salah satu agenda Videla untuk mempercantik citranya. Jonathan Wilson dalam bukunya, Angel With Dirty Face menjelaskan arti penting Piala Dunia bagi rezim militer Videla, yakni menunjukkan kepada dunia bahwa Argentina baik-baik saja serta memperkuat nasionalisme dan menjadi alasan kuat bagi rezim untuk membungkam semua lawan politiknya. Agar semua agenda itu berhasil, Argentina harus menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Apapun caranya.
Konon, Abraham Klein dari Israel ditunjuk sebagai wasit yang bakal memimpin partai final antara Argentina melawan Belanda. Namun pihak tuan rumah meminta pergantian wasit dikarenakan Klein dianggap merugikan Argentina saat kalah di pertandingan fase grup melawan Italia dengan skor 0-1. Permintaan disetujui. Klein digantikan Sergio Gonella. Argentina pun menjadi juara untuk pertama kalinya.
Kontroversi dan intervensi Videla tak mengurangi legitimasi sepakbola indah yang diperagakan Argentina di bawah asuhan Cesar Luis Menotti.
"sepakbola adalah permainan yang lahir dari dan oleh pemain, dengan segala kapasitas mereka untuk berkreasi", ujar Menotti dalam memoarnya. Menottissme, begitulah filosofi sepakbola Menotti disebut. Ia mencoba membangkitkan hegemoni La Nuestra (Our Way) yang menjadi identitas sepakbola Argentina sejak 1930-an hingga 1960-an, di mana keindahan adalah puncak tertinggi permainan.
Bagi Menotti sepakbola bukan sekedar mencari kemenangan. Di dalamnya terdapat semangat kebebasan berekspresi, keindahan dan lekat dengan sejarah perjuangan. Semangat kebersamaan buruh khas Peronisme. Terdengar lucu melihat Menotti, yang berpaham kiri, memenangi gelar dengan gaya permainan atraktifnya berkat campur tangan Videla yang anti-kiri.
Gelar Piala Dunia kedua Argentina disumbangkan pada tahun 1986. Rezim otoriter Videla runtuh dan berganti pemerintahan demokratis. Namun wajah sepakbola Argentina tatkala memenangi gelar keduanya turut berubah drastis.
Carlos Billardo ditunjuk sebagai suksesor Menotti. Keduanya sempat bertemu di Sevilla pada 1983 untuk membahas masa depan Timnas Argentina. Sebagai pendahulu, Menotti menyarankan Billardo untuk tetap teguh pada romantisme La Nuestra yang telah menjadi identitas kebanggaan.
Apa jawaban Billardo?
"Saya suka menjadi juara. Kita harus berpikir bagaimana caranya menjadi juara. Bagi saya runner-up tetaplah sebuah kegagalan"
Ya, bagi Billardo kemenangan adalah segalanya. Apalah arti bermain indah tanpa trofi? Sedari awal ia memosisikan diri sebagai antitesis Menotti. Billardisme, orang menyebut filosofinya itu.
Tidak mengagetkan melihat Argentina cenderung bermain pragmatis pada gelaran Piala Dunia 1986. Billardo lebih suka memainkan skema 3-5-2. Hal yang wajar melihat tujuh orang berbaju strip putih-biru berjejer membentuk benteng pertahanan dalam komando Billardo, serta membiarkan Maradona berkreasi sebebas-bebasnya.
Kerap Tak Bersahabat Dengan sepakbola Ofensif
Jorge Sampaoli menggemparkan sepakbola Amerika Latin bersama Cile. Sampaoli berhasil memberikan gelar Copa America pertama bagi Cile pada 2015. Ironinya ia mengalahkan negaranya sendiri di partai final.
Kala itu Argentina dilatih oleh Gerardo "Tata" Martino. Tata merupakan murid setia Marcelo Bielsa, salah satu pelatih senior Argentina yang juga beraliran Menottisme. Tata Martino mulai dikenal tatkala sentuhan midasnya mampu membangkitkan sepakbola Paraguay hingga mampu menjadi runner-up Copa America 2011.
Bagi Tata, sistem adalah segalanya. Tidak ada pemain yang boleh mengacaukan sistemnya. Senada dengan Bielsa, Tata memainkan skema verticalidad, yakni sebuah gaya permainan ofensif yang mengutamakan kombinasi bola pendek dengan tiga opsi umpan progresif. Haram hukumnya bola berada di udara tanpa alasan khusus.
Dengan verticalidad, Tata Martino menuai kegagalan di Barcelona. Beberapa pihak menuding idealisme Tata mengekang kebebasan Lionel Messi yang dipaksa bermain di sayap kanan. La Pulga tak mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya.
Di Argentina, Tata tetap menempatkan Messi di sayap kanan namun memberinya ruang lebih untuk berkreasi. Ia berdamai dengan idealismenya. Namun ia dikalahkan protagonis lainnya yaitu Sampaoli.
Sampaoli adalah versi lain dari murid Bielsa. Alih-alih terpaku pada sistem, ia cenderung membebaskan pemain untuk berekspresi. Di bawah asuhannya, Timnas Cile bermain menyerang dengan garis pertahanan dan pressing tinggi.
Kesuksesan Sampaoli bersama Cile membuatnya dipinang untuk melatih Timnas Argentina pada 2017. Sama seperti pendahulunya, ia dikaruniai Messi, yang masih berada dalam performa puncaknya. Tangan dingin Sampaoli tatkala melatih Cile tak bisa diulangi bersama Argentina. Pada gelaran Piala Dunia 2018 lalu Argentina dibawah asuhan Sampaoli tampil mengecewakan: kalah telak dari Kroasia 0-3 di fase grup sebelum dihentikan Prancis di perdelapan final.
Entah kebetulan atau tidak. Belakangan La Albiceleste justru moncer manakala dipimpin oleh pelatih dengan filosofi yang cenderung pragmatis.
Terakhir kali Argentina menapaki partai final Piala Dunia adalah pada 2014 lalu. Alejandro Sabella, pelatih kala itu, dikenal sebagai sosok yang mementingkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Di bawah asuhannya Argentina lebih nyaman bermain reaktif, cenderung menunggu untuk memanfaatkan kelengahan lawan yang asyik menyerang. Ia terkadang memainkan Messi sebagai trequartista, memberikan peran yang bebas. Sebagai kompensasi, ia melapisi lini tengah Argentina dengan double pivot Lucas Biglia dan Javier Mascherano. Sabella tak memiliki formasi baku. Namun skema 4-4-2 klasik sering ia mainkan.
Tidak ada pelatih top Argentina yang pantas disebut sebagai imam mazhab Billardisme sekarang selain Diego Simeone. Namun, Sabella dan Lionel Scaloni, pelatih Argentina sekarang, berdiri dalam sisi yang sama dengan Simeone.
Wajah Argentina di bawah Scaloni malah lebih defensif ketimbang Sabella. Ketika mengakhiri dahaga gelar Copa America selama hampir dua dekade pada 2021 lalu, Scaloni menunjukkan sisi Billardisme dengan nyata di partai final. Bermain defensif, keras bahkan agak kasar melawan Brazil yang diperkuat trisula penyerang yang skillfull.
Kekalahan atas Arab Saudi di laga pertama bagi saya mempertegas posisi Scaloni. Argentina di bawah kendalinya tidak nyaman bermain sangat dominan. Borok pertahanan terbuka lebar ketika menyerang. Sebaliknya, Scaloni bermain reaktif melawan Belanda pada perempat final kemarin dengan skema defensif 5-3-2. Argentina justru tampil sangat solid dan menciptakan banyak peluang kendati kalah penguasaan bola.
Bermodalkan sejarah apik, Scaloni dan wajah Billardismenya berpotensi besar memberikan gelar ketiga bagi Argentina tahun ini.
*Penulis adalah seorang karyawan yang kebetulan tergila-gila dengan sepakbola. Bisa dihubungi lewat akun Twitter @TigarisAlifandi
**Tulisan ini merupakan hasil kiriman penulis melalui kolom Pandit Sharing. Segala isi dan opini yang ada dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis.









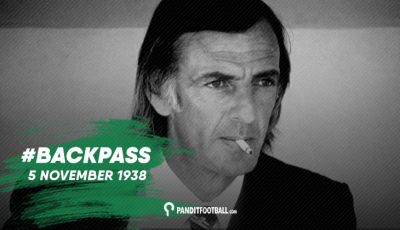

Komentar